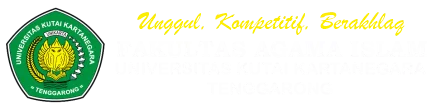BUAT APA KULIAH?: PERNYATAAN DARI SI PINTAR YANG TERDENGAR DUNGU
Oleh: H. Mubarak, S.Pd.I, M.Pd.I*
Di tengah derasnya arus informasi di era digital, sebuah pertanyaan sinis namun populer sering kali terdengar: “Buat apa kuliah? Toh, semua ilmu bisa dipelajari dari internet.” Pernyataan ini yang sering kali dilontarkan oleh individu-individu cerdas yang otodidak, sepintas memang terdengar logis di permukaan. Mereka berargumen bahwa dengan adanya Google, YouTube, kursus daring, dan sumber daya tak terbatas lainnya, institusi pendidikan formal seperti universitas telah menjadi usang. Namun, pandangan ini, meski terkesan pintar, sejatinya merupakan sebuah simplifikasi (kalau bukan: meremehkan!) yang berbahaya dan menunjukkan kesalahpahaman mendasar tentang hakikat pendidikan tinggi. Anggapan bahwa kuliah hanyalah tentang transfer informasi adalah premis dungu yang mengabaikan esensi terpentingnya: pengasahan kompetensi akademik dan pengalaman pendidikan yang terstruktur. Alan Alexander Milne (seorang penulis asal Inggris) mengatakan “Bagi orang yang tidak berpendidikan, huruf A hanyalah sebuah tiga garis.” Pernyataan ini membuka mata kita bahwa tanpa pendidikan, dunia hanyalah kumpulan bentuk dan fenomena tanpa makna. Pendidikanlah yang mengubah persepsi kita, mengubah ‘tiga garis’ acak menjadi huruf ‘A’ sebuah simbol yang menjadi fondasi bahasa, sastra, dan penyebaran gagasan.
Kesalahan fatal dari argumen “semua ilmu bisa dipelajari dari internet” adalah menyamakan antara akses terhadap informasi dengan penguasaan pengetahuan. Internet adalah perpustakaan raksasa yang kacau, yang menyediakan jutaan kepingan puzzle tanpa memberikan gambaran utuh atau cara menyusunnya. Seseorang mungkin bisa menghafal fakta sejarah, rumus, atau teori dari video berdurasi sepuluh menit. Namun, ini hanyalah ilusi pengetahuan. Pendidikan di bangku kuliah, sebaliknya tidak hanya memberikan “apa”-nya, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa”-nya, yang berintikan proses. Proses ini disebut sebagai pengembangan kompetensi akademik. Kompetensi akademik adalah kemampuan untuk berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Ini ditempa melalui kurikulum yang dirancang secara cermat, di mana satu mata kuliah menjadi fondasi bagi mata kuliah lainnya. Mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi dilatih untuk mempertanyakannya, mengujinya melalui metodologi ilmiah, dan membangun argumen yang kokoh berdasarkan bukti. Mereka belajar membedakan antara sumber yang kredibel dan hoaks, antara korelasi dan kausalitas, serta antara opini dan fakta yang terverifikasi. Kemampuan inilah (kemampuan untuk bernalar secara terstruktur) yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh algoritma pencarian atau kursus daring yang bersifat satu arah.
Berikutnya, pandangan tersebut secara naif mengabaikan nilai ekosistem intelektual yang hanya bisa ditemukan di lingkungan kampus. Belajar bukanlah aktivitas soliter (menyendiri). Pertumbuhan intelektual yang paling subur justru terjadi melalui interaksi. Di ruang kelas, seorang mahasiswa dihadapkan pada dosen yang bukan hanya “mengajar”, tetapi juga membimbing, menantang, dan membuka cakrawala baru. Diskusi dengan sesama mahasiswa yang datang dari berbagai latar belakang dan memiliki sudut pandang berbeda adalah “gymnasium” bagi otak yaitu sarana untuk berlatih bersama. Perdebatan sengit tentang sebuah teori, berkolaborasi dalam proyek yang rumit, atau sekadar bertukar pikiran di kantin adalah bagian integral dari pendidikan yang membentuk pola pikir yang fleksibel dan terbuka. Lingkungan ini juga menyediakan akses terhadap sumber daya yang tak ternilai: laboratorium untuk eksperimen, perpustakaan dengan jurnal-jurnal ilmiah, studio praktikum untuk berkarya, serta kesempatan untuk terlibat dalam penelitian bersama para ahli di bidangnya. Pengalaman ini melampaui sekadar perolehan ijazah!. Ini adalah proses magang intelektual dimana seseorang belajar menjadi seorang profesional, seorang ilmuwan, atau seorang pemikir. Jaringan pertemanan dan profesional yang dibangun selama masa kuliah pun, menjadi modal sosial yang tak ternilai sepanjang hidup.
Kuliah adalah sebuah proses tempaan karakter dan disiplin. Tuntutan untuk memenuhi tenggat waktu tugas, tekanan dalam menghadapi ujian, keharusan untuk mengelola waktu antara belajar dan kegiatan non-akademik, bahkan pengalaman menghadapi kegagalan. Semua ini membangun ketahanan, tanggung jawab, dan etos kerja. Seseorang yang belajar secara mandiri mungkin memiliki disiplin diri, tetapi ia tidak diuji secara sistematis dalam lingkungan yang kompetitif dan terstruktur. Justru, dalam tekanan di bangku kuliah seseorang belajar tentang batas kemampuannya dan bagaimana cara melampauinya. Proses ini melahirkan kerendahan hati dan intelektual. Semakin banyak belajar, semakin sadar betapa banyaknya yang belum kita ketahui. Ini adalah penangkal dari jebakan “sok tahu” yang sering menghinggapi para “si pintar” nan otodidak.
Meremehkan pendidikan tinggi dengan dalih bahwa ilmu bisa diperoleh di mana saja adalah sebuah kekeliruan. Ya, bolehlah dikatakan informasi ada di mana-mana, tetapi kebijaksanaan, pemahaman mendalam, dan nalar kritis harus ditempa dan diasah. Kuliah bukanlah sekadar tentang mengumpulkan pengetahuan atau mendapatkan selembar ijazah untuk dipajang di dinding. Ia adalah sebuah investasi dalam membangun “arsitektur” pikiran kita. Ia adalah proses mengubah informasi menjadi pemahaman, mengubah pemahaman menjadi kompetensi, dan pada akhirnya, mengubah seorang individu yang pintar menjadi pribadi yang terdidik dan bijaksana. Pernyataan “buat apa kuliah?” bukanlah cerminan kecerdasan, melainkan sebuah pengakuan atas ketidakmampuan melihat perbedaan antara “sekadar tahu” dan “benar-benar paham”. Mengambil pemahaman dari mahfudzat (kalimat mutiara) yang dulu pernah saya pelajari di bangku pondok pesantren: “Man Lam Yadzuq Dzulla al-Ta’allum Saa’ah, Tajarra’a Dzulla al-Jahli Thula Hayaatih” yang artinya “Barangsiapa belum merasakan susahnya menuntut ilmu barang sejenak, ia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidupnya.” Ungkapan ini menegaskan bahwa kesulitan dalam menuntut ilmu adalah harga yang pantas untuk dibayar.
Di belakang Meja Pengabdian, Unikarta Tenggarong.
*) Penulis adalah Dekan FAI Unikarta Tenggarong